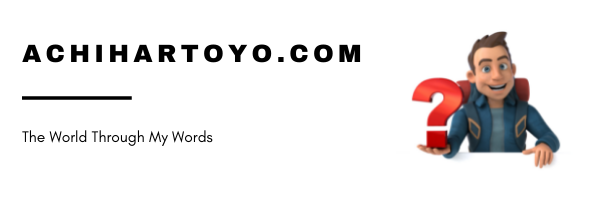Delapan puluh tahun sudah kita merdeka. Lagu kebangsaan tetap sama, bendera tetap merah putih, dan upacara bendera masih bikin anak sekolah berjemur dengan khidmat. Tapi di luar lapangan upacara itu, ada fakta getir yang nggak semua orang mau dengar: jutaan perut di negeri ini masih harus mikir besok makan apa.
Merdeka dari penjajahan sudah lewat tujuh dekade, tapi merdeka dari harga beras yang bikin kening berkerut, rasanya kok masih jauh di depan.
Makanya, ketika Dompet Dhuafa menggelar Sarasehan Tokoh Bangsa dengan tema “Merajut Kebersamaan, Mewujudkan Merdeka dari Kemiskinan”, suasananya bukan sekadar seremonial. Bukan pula ajang foto bareng tokoh. Ini forum yang mencoba membicarakan PR besar bangsa, PR yang nilainya nggak bisa ditulis di papan tulis sekolah karena terlalu banyak nolnya.
Dari tokoh agama sampai aktivis hukum, semua kumpul untuk ngomongin satu hal: bagaimana caranya kemiskinan ini nggak terus-terusan jadi tamu abadi di rumah kita yang katanya sudah merdeka
Merdeka dari Penjajah, Tertawan oleh Harga Beras
Kita ini bangsa yang pernah mengusir penjajah dengan bambu runcing, tapi sekarang kalah sama harga beras yang naik diam-diam kayak maling sandal masjid. Bedanya, maling sandal bisa kita kejar, harga beras? Nah, ini yang bikin sesak napas. Di warung, beras premium mulai mirip harga tiket konser K-Pop. Bahkan beras medium pun udah nggak bisa lagi disebut “murah” tanpa bikin hati berdebar.
Ironisnya, Indonesia punya sawah yang luasnya bikin drone kelelahan kalau mau merekam seluruhnya. Tapi tetap saja, tiap musim paceklik atau cuaca aneh, harga beras melesat. Petani yang panen malah dapat harga rendah, sementara konsumen di kota megap-megap. Jadi, siapa sebenarnya yang merdeka di sini? Sepertinya, hanya para tengkulak dan spekulan yang bisa tidur nyenyak di atas kasur empuk.
Di Sarasehan Tokoh Bangsa, kemiskinan ini dibahas bukan cuma sebagai angka di data BPS, tapi sebagai kenyataan yang dirasakan di meja makan. Ketika beras mahal, efeknya berantai: ongkos makan naik, pedagang kecil susah bertahan, gizi keluarga merosot. Ujung-ujungnya, anak-anak yang harusnya merdeka bermain malah ikut memikirkan lauk apa yang bisa dimasak besok. Dan ini bukan cerita satu-dua rumah tangga, tapi jutaan.
Maka wajar kalau tokoh-tokoh di forum itu sepakat bahwa merdeka dari kemiskinan harusnya satu paket dengan merdeka dari ketergantungan pangan. Soalnya, harga beras ini ibarat sandera: dia nggak kelihatan di TV tiap hari, tapi diam-diam memegang kunci dompet banyak orang. Kalau urusan ini beres, mungkin kita bisa benar-benar mengibarkan bendera sambil berkata, “Akhirnya merdeka, Bung!”, tanpa harus memikirkan harga beras esok pagi.
Negara Paling Dermawan di Dunia, Tapi Kok Tetangga Masih Nunggak Listrik?
Indonesia sudah beberapa tahun ini memegang gelar negara paling dermawan di dunia versi Charities Aid Foundation. Gelar yang terdengar megah, seperti piala bergengsi yang dipajang di lemari kaca ruang tamu. Tapi di balik gelar itu, ada pemandangan sehari-hari yang bikin kita garuk kepala: tetangga sebelah rumah masih gelap-gelapan tiap malam karena listriknya diputus. Bukan karena nggak mau bayar, tapi karena memang uangnya nggak cukup.
Ironinya, kedermawanan orang Indonesia itu nyata. Kotak amal masjid selalu penuh, link donasi online bertebaran di grup WhatsApp, dan kalau ada bencana, truk bantuan bisa datang dari berbagai kota. Tapi rupanya, memberi bantuan ke daerah jauh terasa lebih heroik ketimbang memastikan orang yang tinggal dua rumah dari kita bisa tetap masak nasi tanpa harus nunggu lilin menyala.
Di Sarasehan Tokoh Bangsa, hal ini disorot sebagai tantangan kultural: semangat berbagi kita tinggi, tapi pemerataan bantuan masih bolong-bolong. Zakat, infak, dan sedekah yang terkumpul secara nasional memang fantastis, Rp40,5 triliun pada 2024,tapi distribusinya perlu strategi lebih cermat. Jangan sampai dana yang besar itu hanya jadi pertolongan sesaat, sementara masalah strukturalnya tetap dibiarkan mengendap.
Mungkin ini saatnya kedermawanan kita naik kelas. Dari sekadar memberi amplop lebaran atau sembako, menjadi investasi sosial yang bikin orang benar-benar bangkit. Misalnya, tetangga yang tadinya nggak bisa bayar listrik dibantu modal usaha kecil, supaya bulan depan dia bisa bayar sendiri tagihannya. Kalau itu terjadi, gelar negara paling dermawan nggak cuma terdengar keren di laporan internasional, tapi juga terasa di gang sempit, di rumah kontrakan, dan di hati orang-orang yang hidupnya pelan-pelan berubah.
Masjid Bukan Cuma Tempat Salat, tapi Markas Pemberdayaan
Buat banyak orang, masjid adalah tempat singgah paling aman: mau masuk gratis, mau nangis nggak ditanya-tanya, mau tidur asal nggak mengganggu jamaah pun biasanya dibiarkan. Tapi kalau kita berhenti sebentar dan berpikir, masjid bisa lebih dari sekadar tempat salat dan ceramah. Ia bisa jadi markas besar pemberdayaan umat, sesuatu yang di zaman Rasul dulu sebenarnya sudah terjadi, tapi di sini kadang terlupakan.
Di Sarasehan Tokoh Bangsa, Rahmat Hidayat dari Dewan Masjid Indonesia mengingatkan bahwa Indonesia punya lebih dari 800 ribu masjid. Bayangkan, itu berarti setiap beberapa ratus meter, ada bangunan yang sebenarnya bisa jadi pusat pelatihan keterampilan, perpustakaan kecil, klinik kesehatan, atau bahkan inkubator bisnis mikro. Kalau semua masjid punya satu program pemberdayaan yang jalan, kemiskinan bisa digempur dari gang-gang kecil sampai pelosok desa.
Masalahnya, banyak masjid masih sibuk dengan urusan rutin: pengajian, perayaan hari besar, atau rapat pengurus yang membahas karpet baru. Padahal, kalau mau sedikit saja berinovasi, masjid bisa menampung kelas menjahit untuk ibu-ibu, kursus komputer untuk remaja, atau koperasi pangan untuk warga sekitar. Masjid punya modal sosial, jamaah yang loyal dan siap diajak bergerak—sesuatu yang jarang dimiliki oleh lembaga lain.
Kuncinya memang di mindset: melihat masjid bukan hanya sebagai rumah ibadah, tapi juga sebagai rumah harapan. Kalau peran ini dihidupkan lagi, masjid bisa jadi benteng ekonomi umat, bukan sekadar tempat menunggu azan. Dan siapa tahu, dari sebuah masjid kecil di kampung, lahir pengusaha sukses yang dulu belajar keterampilan di serambi masjid. Itu baru namanya salatnya jalan, ekonominya pun ikut makmur.
Filantropi: Dari Bagi-bagi Sembako ke Mengubah Nasib Bangsa

Filantropi di Indonesia itu ibarat air hujan di musim penghujan: deras, melimpah, dan sering datang tanpa diminta. Tapi, seperti air hujan, kalau nggak dialirkan dengan baik, dia bisa menggenang dan nggak membawa manfaat maksimal. Bagi-bagi sembako jelas baik, tapi kalau cuma itu yang kita lakukan, efeknya mirip obat pereda nyeri: reda sebentar, besok kambuh lagi.
Di Sarasehan Tokoh Bangsa, para tokoh sepakat bahwa filantropi harus naik level. Artinya, dari aksi sesaat menjadi strategi panjang. Misalnya, dana zakat bukan cuma untuk memenuhi kebutuhan mendesak, tapi juga membiayai pelatihan kerja, membangun akses pasar untuk produk lokal, atau mendukung teknologi pertanian. Jadi, penerima bantuan nggak terus-terusan bergantung, tapi punya jalan untuk mandiri.
Dompet Dhuafa memberi contoh, bahwa sinergi lintas sektor, dari tokoh agama, akademisi, pelaku usaha, sampai masyarakat sipil, bisa membuat filantropi menjadi mesin penggerak perubahan. Karena pada akhirnya, membantu orang itu bukan sekadar memberi mereka makan hari ini, tapi memastikan mereka bisa makan esok dan seterusnya tanpa harus menunggu uluran tangan lagi. Itu baru namanya mengubah nasib bangsa, bukan sekadar membagi nasi bungkus.
80 Tahun Merdeka, Saatnya Kemiskinan Masuk Museum Sejarah
Delapan puluh tahun lalu, kita mengibarkan bendera dengan janji bahwa bangsa ini akan berdiri tegak, merdeka, dan bermartabat. Tapi faktanya, kemiskinan masih mondar-mandir di kampung, kota, bahkan di sudut-sudut jalan yang tiap pagi kita lewati. Kalau kemiskinan ini manusia, mungkin dia sudah jadi warga senior yang hafal semua jalan tikus di negeri ini.
Karena itu, gagasan “kemiskinan masuk museum” bukan sekadar kiasan puitis, tapi cita-cita serius. Bayangkan, di masa depan, anak-anak sekolah datang ke museum, melihat foto-foto rumah reyot dan antrean bantuan sembako, lalu bertanya, “Dulu beneran ada orang yang hidup begini?” Dan gurunya bisa menjawab, “Iya, tapi itu zaman dulu, sebelum bangsa ini bener-bener kompak memberantasnya.”
Forum seperti Sarasehan Tokoh Bangsa ingin mendorong komitmen itu, bahwa pengentasan kemiskinan bukan proyek lima tahun sekali, tapi perjuangan yang dijalankan terus-menerus. Kita punya sumber daya, punya modal sosial, dan punya jutaan hati yang mau berbagi. Tinggal satu yang harus dikerjakan bersama: memastikan kemiskinan kehilangan alamatnya di Indonesia. Biar kalau pun mau datang lagi, dia nyasar, karena semua pintu sudah tertutup rapat untuknya.