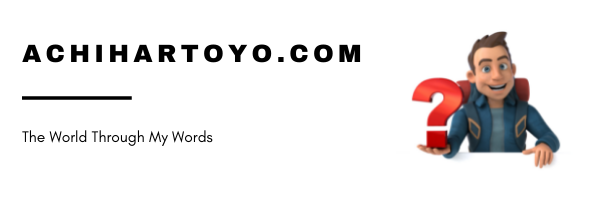Ramadan selalu punya dua wajah. Yang pertama: diskon kurma, jadwal bukber, dan story Instagram berisi kutipan hadis dengan font estetik. Yang kedua: wajah yang lebih sunyi. Tentang orang-orang yang menghitung ulang isi dompetnya sambil berharap harga beras tidak ikut naik lagi besok pagi. Di antara dua wajah itu, kita sering berdiri gamang: ingin terlihat saleh, tapi juga sedang sama-sama berjuang.
Tahun ini, Ramadan datang dengan napas yang sedikit lebih berat. Ekonomi belum sepenuhnya pulih, banjir dan longsor di Sumatra menyisakan pilu, dan kabar dari Palestina masih terasa seperti berita yang tak pernah benar-benar selesai.
Dalam situasi seperti ini, membicarakan zakat terasa berbeda. Ia bukan cuma kewajiban fiqh yang ditunaikan setahun sekali, melainkan pertanyaan sederhana: setelah menahan lapar seharian, apa kita juga mau menahan diri untuk tidak cuek?
Maka ketika muncul slogan “Berzakat Itu Kalcer”, saya sempat tersenyum kecil. Istilah kekinian bertemu rukun Islam. Kombinasi yang bagi sebagian orang mungkin terdengar nyeleneh. Tapi barangkali memang itu poinnya.
Kalau budaya hari ini dibentuk oleh apa yang kita ulang-ulang dan rayakan bersama, kenapa tidak menjadikan berbagi sebagai sesuatu yang biasa, ringan, dan dilakukan tanpa perlu menunggu momen viral? Karena zakat, pada akhirnya, bukan cuma soal transferan. Ia soal cara kita memaknai keberadaan orang lain dalam hidup kita.
Ramadan di Tengah Luka, Ketika Solidaritas Tak Bisa Ditunda
Ramadan kali ini tidak datang dalam suasana yang sepenuhnya khusyuk. Ia hadir di antara berita banjir di Aceh, longsor di Sumatra Barat, dan dapur-dapur yang apinya menyala lebih pelan karena harga kebutuhan pokok yang makin tidak ramah.
Kita bisa saja tetap berbicara tentang target khatam Al-Qur’an dan jadwal tarawih tercepat, tapi di luar sana ada orang-orang yang bahkan belum selesai membereskan lumpur dari ruang tamunya. Dalam situasi seperti ini, solidaritas bukan lagi pilihan moral yang manis, ia kebutuhan yang mendesak.
Di titik itulah zakat menemukan relevansinya yang paling nyata. Ia bukan cuma angka 2,5 persen yang dihitung dengan kalkulator, melainkan mekanisme sosial yang sejak awal dirancang untuk merawat keseimbangan.
Ketika kesenjangan terasa makin lebar, zakat bekerja sebagai jembatan: dari yang lapang ke yang sempit, dari yang cukup ke yang kekurangan. Masalahnya, jembatan itu hanya akan berdiri kokoh kalau kita benar-benar melangkah di atasnya, bukan sekadar mengunggah niat baik di story.
Ramadan seharusnya mengajarkan kita satu hal sederhana: menahan diri bukan cuma dari makan dan minum, tapi juga dari sikap masa bodoh. “Berzakat Itu Kalcer” terasa relevan justru karena luka sosial tak bisa menunggu sampai kita mapan dulu.
Kalau budaya berarti sesuatu yang kita lakukan berulang-ulang, maka mungkin inilah saatnya menjadikan solidaritas sebagai kebiasaan, bukan reaksi musiman setiap kali musibah muncul di linimasa.
Dari Tebar Zakat sampai Ber-ojol, Ketika Program Bukan Sekadar Program
Sering kali kita mendengar daftar program Ramadan seperti mendengar rundown acara: panjang, rapi, lalu selesai. Tebar Zakat Fitrah, Yatim Remember, Ber-ojol, Recovery Sumatra, Borong Dagangan Saudaramu, hingga Mudik Kalcer, namanya terdengar catchy, mudah diingat, bahkan Instagramable. Tapi di balik nama-nama itu ada realitas yang tidak selalu estetik: ada anak yatim yang butuh keberlanjutan, bukan cuma bingkisan; ada pengemudi ojek online yang kendaraannya harus tetap prima supaya dapurnya tak ikut mogok.
Di sinilah bedanya gerakan dengan gimmick. Program yang baik tidak berhenti pada seremoni simbolis atau foto serah terima donasi. Ia harus menjawab pertanyaan paling sederhana: setelah bantuan diberikan, apa yang berubah? Apakah mustahik sekadar menerima, atau benar-benar didorong untuk bangkit dan berdaya? Kalau zakat hanya berhenti sebagai penyaluran, ia mungkin meringankan. Tapi ketika dikelola dengan arah pemberdayaan, ia bisa menguatkan.
Kita hidup di era yang gemar mengarsipkan kebaikan dalam bentuk konten. Padahal, kebaikan yang paling berdampak justru sering kali tidak ramai. Ia bekerja pelan, terstruktur, dan konsisten. Maka ketika Ramadan menjadi momentum untuk menggerakkan berbagai program sosial, yang perlu kita jaga bukan cuma euforianya, melainkan keberlanjutannya. Karena berbagi yang benar-benar “kalcer” bukan yang paling viral, melainkan yang paling terasa manfaatnya.
Kolaborasi Itu Kalcer, Negara, Bank Syariah, Relawan, dan Kita
Potensi zakat Indonesia sering disebut-sebut besar. Angkanya fantastis, grafiknya menjanjikan. Tapi potensi, kalau tidak dikelola bersama, hanya akan jadi optimisme di atas kertas. Zakat bukan urusan satu lembaga saja, apalagi sekadar urusan individu yang merasa sudah “lunas kewajiban”. Ia butuh ekosistem: regulasi yang jelas, lembaga yang profesional, perbankan yang memudahkan, relawan yang bergerak, dan masyarakat yang percaya.
Di meja yang sama, negara bicara roadmap ZISWAF, perbankan syariah bicara kolaborasi layanan, lembaga zakat bicara transparansi dan akuntabilitas, relawan bicara pengalaman di lapangan. Kedengarannya formal. Tapi justru di situlah pentingnya. Karena kebaikan yang ingin menjadi budaya tidak bisa berdiri di atas spontanitas saja. Ia perlu sistem, perlu tata kelola, perlu kepercayaan publik yang dijaga pelan-pelan seperti merawat api kecil agar tidak padam.
Dan mungkin, di titik ini kita perlu jujur: zakat bukan cuma soal hubungan vertikal dengan Tuhan, tapi juga kontrak sosial antarmanusia. “Berzakat Itu Kalcer” menjadi masuk akal ketika kolaborasi tidak berhenti sebagai jargon. Saat semua pihak (dari regulator sampai donatur recehan).merasa punya peran, di situlah berbagi berubah dari kewajiban personal menjadi gerakan kolektif. Bukan lagi aksi musiman, tapi identitas bersama.
Dari Story ke Aksi: Saatnya Donasi Nggak Cuma Jadi Wacana
Kita ini generasi yang cepat sekali mengetik “Masyaallah” dan “Semoga Allah mudahkan” di kolom komentar. Cepat juga membagikan poster donasi ke story, lengkap dengan emoji tangan berdoa. Tapi Ramadan selalu menuntut lebih dari sekadar empati digital. Ia meminta kita turun satu langkah lagi: dari niat baik ke tindakan nyata. Karena kebaikan yang hanya berhenti di layar, sering kali tak pernah benar-benar sampai ke tangan yang membutuhkan.
Kalau “Berzakat Itu Kalcer” ingin jadi budaya, maka ia harus dibuat mudah, ringan, dan tidak ribet. Dompet Dhuafa sudah menyiapkan banyak kanal donasi, mulai dari aplikasi, transfer bank, hingga layanan jemput zakat. Bahkan kolaborasi dengan Maybank Syariah menghadirkan kemudahan berdonasi lewat layanan perbankan yang terintegrasi.
Artinya, alasan klasik seperti “nanti dulu deh, ribet” sebenarnya sudah makin sulit dipertahankan. Tinggal mau atau tidak.
Ramadan tidak pernah menunggu kita merasa cukup dulu untuk berbagi. Justru di saat terasa pas-pasan, di situlah empati diuji. Jadi kalau selama ini zakat cuma jadi caption atau reminder tahunan, mungkin ini waktunya menjadikannya aksi yang konkret. Transfernya mungkin sederhana, tapi dampaknya bisa panjang. Dan kalau berbagi memang mau dijadikan “kalcer”, mari mulai dari langkah paling praktis: tunaikan zakat, infak, dan sedekahmu melalui Dompet Dhuafa (termasuk lewat layanan Maybank) lalu biarkan kebaikan bekerja lebih jauh dari yang bisa kita lihat.