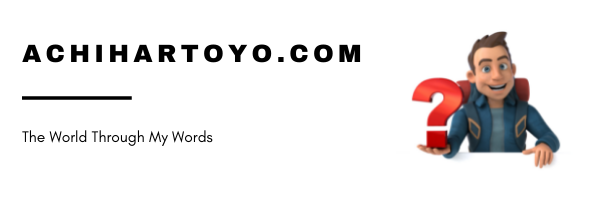Saya duduk di ballroom Nusantara TV siang itu, di tengah paparan data, grafik, dan kata-kata besar tentang kemiskinan, pemberdayaan, dan masa depan filantropi Indonesia. Indonesia Humanitarian Summit 2025 terdengar seperti acara yang rapi, terstruktur, dan optimistis. Namun di balik semua itu, ada satu perasaan yang sulit diabaikan: rasa tidak nyaman.
Bukan karena acaranya buruk, justru sebaliknya, karena banyak hal yang disampaikan terasa terlalu dekat dengan realitas yang selama ini kita jalani, tapi sering kita sangkal.
Data demi data dipresentasikan. Angka kemiskinan disebut menurun. Penghargaan diraih. Program berjalan. Tapi di luar ruangan ber-AC itu, kita tahu cerita yang lain tetap berlangsung: kelas menengah yang pelan-pelan menjadi rapuh, orang-orang bekerja lebih keras dengan hasil yang makin tipis, dan hidup yang terasa makin mahal tanpa benar-benar memberi rasa aman.
Di titik ini, saya menyadari bahwa persoalan kemiskinan hari ini bukan lagi sekadar soal siapa yang miskin dan siapa yang tidak, melainkan siapa yang bisa jatuh kapan saja.
Mungkin itulah mengapa tema Empowerment to the Next Level terasa relevan, sekaligus menantang. Karena filantropi tak lagi cukup hanya hadir sebagai tangan yang memberi, tapi harus naik kelas menjadi sistem yang memberdayakan. Ketika negara tak selalu hadir tepat waktu, solidaritas publik dipanggil untuk bekerja lebih cerdas, lebih terukur, dan lebih berkelanjutan. Bukan untuk menggantikan negara, tetapi untuk menutup celah-celah yang makin nyata dalam kehidupan sehari-hari.
Kemiskinan yang Turun di Data, Naik di Kehidupan Sehari-hari
Di layar besar ballroom, angka kemiskinan ditampilkan dengan rapi. Persentasenya turun. Grafiknya landai. Presenternya tenang. Data resmi selalu punya kemampuan menenangkan publik: seolah masalah besar bisa dikecilkan dengan satuan persen.
Padahal, di luar layar itu, banyak orang tidak benar-benar merasa lebih sejahtera. Mereka hanya belajar bertahan dengan versi hidup yang makin disederhanakan, mengurangi belanja, menunda rencana, dan menganggap cemas sebagai bagian normal dari rutinitas.
Masalahnya, kemiskinan hari ini tidak selalu hadir sebagai kekurangan yang kasat mata. Ia tidak selalu datang dalam rupa rumah reyot atau perut lapar yang ekstrem. Ia hadir lebih halus: tabungan yang habis pelan-pelan, cicilan yang terasa makin berat, biaya hidup yang naik tanpa negosiasi.
Banyak orang secara statistik masih “tidak miskin”, tapi secara psikologis hidup dalam ketidakpastian. Mereka bukan keluar dari kemiskinan; mereka hanya berjalan di tepinya.
Di sinilah data sering kalah cepat dari kenyataan. Statistik membutuhkan metodologi, waktu, dan jarak. Sementara hidup berjalan setiap hari tanpa jeda. Ketika angka kemiskinan turun, tapi rasa aman sosial tidak ikut naik, ada sesuatu yang luput dari perhitungan. Dan barangkali, yang luput itu bukan kesalahan angka, melainkan cara kita memahami kemiskinan sebagai pengalaman hidup, bukan sekadar kategori administratif.
Kelas Menengah yang Bekerja Keras tapi Tetap Rentan
Kelas menengah sering digambarkan sebagai penyangga ekonomi, kelompok yang dianggap “aman” karena masih bisa membayar cicilan, liburan setahun sekali, dan sesekali ngopi tanpa rasa bersalah. Tapi di balik citra itu, banyak dari mereka hidup dalam keseimbangan yang rapuh. Satu PHK, satu sakit serius, atau satu krisis ekonomi kecil saja cukup untuk menggoyahkan semuanya.
Mereka bekerja keras bukan untuk naik kelas, melainkan agar tidak turun kelas. Yang membuat situasi ini semakin pelik adalah absennya ruang jeda. Kelas menengah dituntut selalu kuat karena dianggap belum miskin. Mereka jarang masuk radar bantuan sosial, tapi juga tak cukup mapan untuk merasa aman. Hidup di wilayah abu-abu ini membuat banyak orang memilih diam, nenyembunyikan lelah, menormalisasi cemas, dan menganggap kegagalan sebagai urusan pribadi, bukan persoalan struktural.
Di titik inilah kita mulai melihat kemiskinan sebagai proses, bukan status. Bukan soal sudah miskin atau belum, tapi seberapa dekat seseorang dengan jurang itu. Kelas menengah hari ini bukan sekadar kelompok pendukung ekonomi nasional; mereka adalah barisan paling rentan jika sistem gagal memberi perlindungan.
Dan ketika negara tak selalu hadir untuk mencegah kejatuhan itu, beban sosial pelan-pelan berpindah ke ruang solidaritas, ke filantropi yang dituntut bukan hanya dermawan, tapi juga strategis.
Dari Bantuan Sesaat ke Pemberdayaan yang Berkelanjutan
Bantuan selalu terasa baik, dan sering kali memang dibutuhkan. Dalam situasi darurat, ia menyelamatkan hari, bahkan nyawa. Tapi bantuan juga punya batas: ia berhenti di titik ketika bantuan itu habis. Di sinilah pemberdayaan mulai relevan, bukan sebagai istilah keren dalam proposal, melainkan sebagai upaya membuat seseorang tidak perlu kembali ke antrean bantuan yang sama tahun depan. Pemberdayaan menuntut kesabaran, proses panjang, dan hasil yang tak selalu bisa dipamerkan dengan cepat.
Di acara itu, istilah empowerment berulang kali disebut, seolah menjadi jawaban atas semua persoalan. Namun justru di situlah tantangannya. Pemberdayaan bukan sekadar pelatihan, bukan pula hanya modal usaha atau pendampingan singkat. Ia menuntut ekosistem: akses pasar, keberlanjutan pendapatan, literasi keuangan, dan kehadiran yang konsisten. Tanpa itu, pemberdayaan berisiko menjadi bantuan yang diberi nama lain, terlihat lebih canggih, tapi sama rapuhnya.
Ketika filantropi diminta naik kelas, yang diminta bukan sekadar memperbesar dana yang terkumpul, melainkan memperdalam dampaknya. Dari menghitung berapa banyak yang dibantu, ke mengukur seberapa jauh hidup mereka benar-benar berubah. Ini bukan pekerjaan mudah, dan tidak selalu populer. Tapi mungkin memang di situlah letak kedewasaan filantropi: berani meninggalkan solusi cepat demi perubahan yang pelan, tapi lebih tahan lama.
Saat Solidaritas Harus Dikelola, Bukan Sekadar Diniatkan
Solidaritas sering kita banggakan sebagai identitas bangsa. Kita merasa mudah tergerak, cepat membantu, dan ringan tangan saat melihat kesulitan orang lain. Tapi solidaritas yang hanya bergantung pada niat baik mudah lelah. Ia datang saat emosi tersentuh, lalu pergi ketika perhatian berpindah. Di tengah persoalan kemiskinan yang makin kompleks dan berlapis, solidaritas semacam ini tak cukup kuat untuk menopang perubahan jangka panjang.
Di titik inilah pengelolaan menjadi penting. Solidaritas perlu sistem agar tidak habis di satu momen. Ia perlu tata kelola, akuntabilitas, dan strategi agar bantuan tak berhenti sebagai peristiwa, melainkan berlanjut sebagai proses. Lembaga filantropi bekerja di ruang ini, mengubah empati menjadi program, niat baik menjadi dampak, dan donasi menjadi jalan keluar yang lebih berkelanjutan bagi mereka yang hidup di batas rentan.
Mungkin itulah makna filantropi yang diminta naik kelas. Bukan karena kedermawanan kita kurang, tapi karena tantangan sosial hari ini terlalu besar untuk ditangani secara spontan. Jika solidaritas ingin bertahan lebih lama dari rasa iba, ia perlu dititipkan pada sistem yang bisa dipercaya. Dan di sanalah kita, sebagai warga biasa, punya pilihan sederhana namun berarti: mendukung filantropi yang bekerja serius, terukur, dan berpihak pada pemberdayaan, seperti yang terus diupayakan Dompet Dhuafa. Bukan sekadar memberi, tapi ikut memastikan bahwa harapan punya peluang untuk bertahan.
Sebab di dunia yang makin rapuh, mungkin yang paling berbahaya bukan kurangnya niat baik, melainkan keyakinan bahwa niat saja sudah cukup.