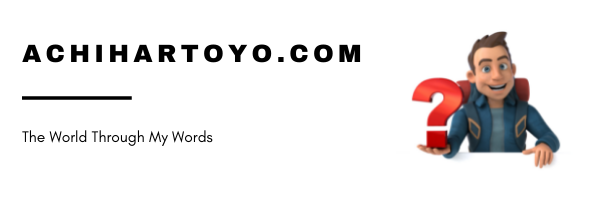Gizi, kata yang sering kita dengar sejak kecil, sering kali hanya diartikan sebagai apa yang kita makan: karbohidrat, protein, lemak, dan sayur-mayur. Tapi semakin hari, kita menyadari bahwa gizi adalah medan yang lebih luas, lebih kompleks, dan lebih sunyi dari sekadar isi piring. Ia tidak hanya menyangkut angka-angka dalam tabel kalori, tapi juga tentang siapa yang boleh bicara dan siapa yang didengar. Di era ketika influencer diet lebih dipercaya daripada ahli gizi dengan STR, gizi justru menjadi perkara kultural, bukan sekadar ilmiah.
Dari sunyi itulah Ayu Fauzziyah memulai. Di Sidoarjo, di tengah kesibukan sebagai dosen gizi dan ibu rumah tangga, ia menciptakan Gizipedia. Kanal edukasi ini pelan-pelan menembus algoritma media sosial yang lebih gemar menyoroti tubuh langsing ketimbang isi kepala. Ia tidak berteriak, tidak membentak dunia dengan jargon viral. Ia menulis, menjelaskan, dan mengulang, bahkan untuk pertanyaan yang sama. Sementara para buzzer diet menjual ketakutan dan mimpi tubuh ideal, Ayu menyalakan lilin kecil bernama literasi.
Ketika Gizi Tak Lagi Soal Makanan
Di posyandu atau rumah lansia, gizi bukan tentang tren atau kecantikan. Ia adalah pertanyaan sehari-hari: bagaimana cara makan sebutir telur agar cukup untuk dua orang? Apakah garam yang dikurangi bisa mencegah tekanan darah tinggi? Di balik papan tulis berisi rumus GPAD (Gross Product per Agricultural Day) atau Angka Kecukupan Gizi, ada tubuh-tubuh renta yang kerap dilupakan, yang diam-diam menua dalam kekurangan. Di sinilah ilmu bertemu empati, dan di sinilah aktivisme tak selalu bermula dari demonstrasi, tapi dari selembar infografik yang jujur.
Tapi gizi tak pernah berdiri sendiri. Ia terhubung dengan politik pangan, sistem pendidikan, hingga cara kita memandang otoritas. Ketika Ayu menyebut dirinya lebih sebagai penyambung lidah ilmu daripada bintang media sosial, ia sedang mengingatkan bahwa informasi yang benar kerap kalah dari informasi yang menarik. Dan bahwa mempopulerkan kebenaran jauh lebih sulit daripada memviralkan ketakutan. Dalam kerja sunyinya, Gizipedia menjadi semacam perlawanan kultural yang tak gaduh, tapi gigih.
Ia pernah menerima penghargaan. Tapi seperti yang ia tahu, dan kita pun paham, penghargaan tidak mengenyangkan. Yang lebih dibutuhkan bukanlah plakat, tetapi pergeseran cara berpikir. Bahwa gizi adalah hak, bukan privilese. Dan bahwa hak itu tidak akan selesai hanya dengan label sehat atau diet rendah gula, tapi dengan distribusi ilmu yang adil. Di situlah gizi belum selesai. Dan barangkali memang tidak akan pernah sepenuhnya selesai, selama kita masih mengukur kesehatan hanya dari yang tampak di permukaan.
Ayu, Sidoarjo, dan Sunyi yang Panjang

Ayu tak seperti pegiat media sosial kebanyakan. Ia tidak sibuk mengejar impresi, tak peduli pada jumlah likes, dan tidak sibuk menyusun angle kamera agar wajahnya terlihat lebih bersinar. Ia lebih tertarik pada siapa yang membaca, siapa yang bertanya, dan siapa yang diam-diam mencatat. Dari rumahnya di Sidoarjo, ia mencicil literasi gizi dengan cara yang tidak glamor. Membuat konten edukatif, menjawab DM dari orang asing, dan menyusun narasi berdasarkan data, bukan emosi.
Sunyi adalah ritme yang tak asing baginya. Ia tahu betul bahwa bicara tentang gizi di Indonesia bukan hal yang ramai. Tak sepopuler skincare, tak semenarik tips diet Korea. Tapi ia bertahan. Karena Ayu tahu bahwa sunyi bukan berarti sia-sia. Di balik satu infografik yang hanya dilihat lima ratus orang, bisa jadi ada seorang ibu di pelosok desa yang akhirnya tahu bahwa bayinya stunting bukan karena kutukan, tapi karena ketidaktahuan. Dan di situlah edukasi bekerja secara perlahan, tak kasat mata, tapi membekas.
Ia bukan tanpa kritik. Ada yang bilang pendekatannya terlalu akademik, terlalu halus untuk menembus masyarakat bawah. Tapi Ayu paham satu hal: kebenaran yang dipaksakan justru bisa ditolak. Maka ia memilih pendekatan yang membumi. Ia tak menyederhanakan hingga menyesatkan, tapi juga tak menggurui hingga menjauhkan. Ia tahu bahwa edukasi gizi bukan soal menyampaikan fakta, tapi bagaimana mengaitkan fakta itu dengan realitas hidup sehari-hari. Dengan keterbatasan. Dengan keyakinan. Dengan budaya makan yang diwariskan turun-temurun.
Di tengah masyarakat yang mulai terbiasa dengan suara-suara keras, Ayu memilih jadi gema kecil yang konsisten. Ia tahu bahwa sistem kesehatan kita terlalu besar untuk diubah sendiri. Tapi ia percaya pada efek domino. Satu orang tercerahkan bisa menyentuh dua lainnya. Dua bisa menjadi lima. Lima bisa menjadi gerakan. Dan mungkin di sinilah titik paling penting dari perannya: ia tidak mencari perubahan besar yang instan, tapi mengupayakan perubahan kecil yang bertahan.
Sidoarjo menjadi latarnya, tapi sebenarnya kerja Ayu melampaui batas geografis. Ia hadir di Instagram, TikTok, dan YouTube bukan untuk menjadi terkenal, tapi untuk memastikan bahwa suara tentang gizi bisa ditemukan oleh siapa saja yang mencarinya. Di sela kesibukan kampus dan rumah, ia tetap menulis. Dan dari sunyi itulah, suara Ayu tumbuh, merambat, lalu diam-diam menyentuh mereka yang lelah menebak-nebak kebenaran dari tubuhnya sendiri.
Papan Rumus dan Sebungkus Telur
Papan tulis di sebuah kelas gizi mungkin dipenuhi angka: kebutuhan kalori, persentase karbohidrat, tabel berat badan ideal, grafik stunting. Semua rumus itu tampak rapi, nyaris klinis. Tapi angka-angka itu kerap membentur tembok kenyataan ketika seorang ibu bertanya, kalau semua serba mahal, saya harus pilih beli apa dulu, beras, minyak, atau telur?
Gizi dalam kenyataannya lebih sering ditentukan oleh harga pasar ketimbang ilmu gizi itu sendiri. Di banyak rumah tangga, rumus yang berlaku bukan AKG, melainkan rumus ekonomi rumah tangga. Cukupkan uang segitu untuk makan hari ini dan besok, kalau bisa sekalian beli sabun dan bayar utang warung. Maka di balik setiap sebutir telur yang masuk ke piring, ada negosiasi panjang, kadang dengan kantong, kadang dengan hati.
Sebungkus telur bisa berarti kemewahan tersembunyi. Ia tak hanya membawa protein hewani, tapi juga harapan. Anak bisa tumbuh sehat, bisa belajar tanpa lelah, bisa duduk di sekolah tanpa pingsan. Namun harapan itu rapuh ketika distribusi pangan tak merata, harga pangan bergantung musim, dan para petani atau peternak tak mendapat perlindungan yang layak.
Di sinilah papan rumus dan sebungkus telur bertemu dalam ironi. Ilmu gizi tak pernah salah, tapi sering tak bisa menjangkau realitas. Di buku teks, kita diajarkan pentingnya zat besi, asam folat, dan vitamin A. Tapi di dunia nyata, seseorang bisa hidup bertahun-tahun tanpa tahu bahwa kelelahan kronisnya berasal dari anemia, atau bahwa anaknya kurus bukan karena bawaan lahir melainkan kekurangan protein.
Ayu dan pejuang literasi gizi lainnya mencoba menjembatani dua dunia ini. Dunia papan rumus dan dunia piring nasi seadanya. Mereka mengupayakan agar sains bisa turun ke dapur, agar kebijakan bisa menyentuh meja makan. Mungkin belum sempurna. Tapi dari sebungkus telur yang akhirnya bisa masuk ke satu piring, kita belajar bahwa gizi bukan hanya urusan angka. Ia adalah urusan keberpihakan, sistem pangan, dan kemanusiaan yang berkelanjutan.
Ketika Gizi Menjadi Gerakan Kultural
Satu hal yang sering luput dari kampanye gizi nasional adalah kenyataan bahwa makan bukan hanya soal nutrisi. Makan adalah budaya. Ia menyimpan memori kolektif, kebiasaan turun-temurun, rasa aman dalam rutinitas, bahkan identitas. Maka ketika Ayu dan teman-temannya berbicara tentang gizi, mereka tak hanya membawa data, tapi juga membawa cerita. Mereka tidak hanya mengubah menu, tapi juga mencoba menata ulang cara kita memaknai makanan.
Di banyak desa, gizi tidak datang lewat piring empat sehat lima sempurna, tapi lewat sayur lodeh yang dimasak ibu, nasi aking yang direndam air panas, atau sisa lauk semalam yang dibagi ulang. Gizi dalam konteks ini adalah perlawanan diam-diam terhadap kelangkaan. Maka memperkenalkan pola makan sehat bukan semata membagi brosur atau seminar, tapi masuk ke dapur, mendengar alasan mengapa orang lebih memilih gorengan daripada buah.
Gerakan kultural ini membutuhkan kesabaran. Tidak cukup mengutuk kebiasaan jajan micin jika kita tidak memahami bahwa jajanan itu lebih murah dan lebih mudah diakses ketimbang satu potong pepaya. Tidak cukup menyerukan diet seimbang tanpa memastikan bahan pangan lokal seperti daun kelor, tempe, atau ikan kecil dihargai dan tersedia. Karena budaya makan dibentuk oleh sejarah panjang, oleh ekonomi, oleh rasa takut lapar, dan oleh tradisi menyiasati.
Ayu sendiri memulai dari hal paling dasar. Mendongeng. Ia menulis cerita anak tentang gizi, membacakan buku di posyandu, mendatangi warung dan bertanya apa yang sering dibeli anak-anak. Dari sana, ia merangkai pendekatan yang tak menyalahkan, tapi merangkul. Ia tidak datang sebagai ahli gizi, melainkan sebagai tetangga. Sebab ia tahu, perubahan tidak bisa dipaksakan dari atas. Ia harus tumbuh dari bawah, dari meja makan keluarga, dari obrolan dapur, dari kebiasaan yang dikaji ulang perlahan.
Maka gerakan gizi tak lagi hanya berada di laboratorium dan kantor kementerian. Tapi juga di warung kopi, di grup WhatsApp ibu-ibu, di arisan RT, bahkan di lagu anak-anak yang mengajarkan bahwa sayur bukan musuh. Di sana, gizi hidup sebagai narasi, bukan sekadar angka. Dan dari situlah perubahan yang paling bertahan lama bisa tumbuh.
Sebuah Penghargaan yang Tak Mengenyangkan
Suatu hari Ayu diundang menerima penghargaan. Ia diminta berdiri di atas panggung, memakai blus terbaiknya, dan menjawab pertanyaan dari jurnalis yang sebelumnya tak pernah menginjak tanah desanya. Lampu sorot menyoroti wajahnya, dan di belakangnya terpampang spanduk besar tentang inovasi sosial. Ia tersenyum, bukan karena bangga, tapi karena sedikit kecut.
Sebab penghargaan itu, seperti banyak penghargaan lainnya, tidak pernah datang bersamaan dengan perbaikan sistemik. Setelah acara usai, Ayu kembali ke Sidoarjo, ke ruang belajar seadanya, ke dusun yang masih mencampur kopi dengan nasi karena itu lebih murah dan membuat kenyang. Ia kembali ke anak-anak yang datang dengan perut kosong dan guru-guru yang harus mencari cara agar pelajaran tidak terhenti karena listrik padam.
Di dunia yang mengagungkan metrik dan indikator, kerja seperti yang dilakukan Ayu sering kali dinilai dari berapa banyak anak yang diberi makan tambahan, berapa berat badan yang naik, berapa kunjungan yang tercatat. Tapi tidak ada alat ukur yang mampu mencatat kesunyian panjang di balik perjuangan itu. Bagaimana rasanya menjelaskan pada seorang ibu bahwa anaknya stunting bukan karena ia tidak sayang, tapi karena sistem yang lebih besar dari dirinya telah gagal mendukungnya.
Penghargaan tak pernah bisa menggantikan kebutuhan paling dasar. Harga bahan pangan yang terjangkau, distribusi yang merata, dan pengakuan bahwa urusan gizi bukan cuma pekerjaan dinas kesehatan. Gizi adalah kerja kolektif, lintas sektor, lintas waktu, lintas hati. Ia bukan soal piring semata, tapi tentang siapa yang duduk di meja makan, siapa yang bisa menyuap, dan siapa yang harus menahan lapar.
Tulisan ini mungkin tak menyelesaikan masalah. Tapi seperti Ayu dan ribuan pegiat gizi lain yang memilih bekerja dalam diam, barangkali yang paling penting bukan menyelesaikan, tapi merawat harapan. Karena di negeri seperti ini, harapan yang terus hidup, meski tak pernah kenyang sepenuhnya, adalah gizi paling penting agar kita tetap bisa berjalan.