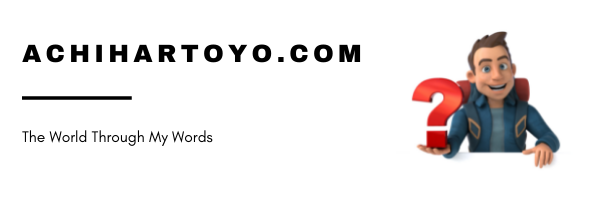Kamis sore itu, di Winners Backyard, Pondok Pinang, saya duduk di antara obrolan ringan, senyum yang berseliweran, dan secangkir minuman yang mulai dingin. Acara bertajuk Harmoni di Ramadan: Merajut Cerita dari Sumatra terdengar hangat sejak judulnya, tapi semakin malam, saya sadar: yang sedang dirajut di sini bukan sekadar cerita, melainkan juga rasa bersalah halus, karena di saat kami nyaman berbincang, ada orang-orang di Sumatra yang masih menyambut Ramadan dari balik tenda.
Saya datang sebagai undangan, pulang sebagai orang yang kepalanya sedikit lebih penuh. Cerita tentang rumah sementara, tenda pengungsian, dan mata-mata yang tetap menyala di tengah kehilangan membuat Ramadan tak lagi terasa sebatas jadwal imsak dan buka puasa. Di ruangan itu, kepedulian tidak dipresentasikan sebagai slogan, melainkan sebagai keputusan: mau diam, atau ikut bergerak. Dan saya tahu, setelah sore itu, Ramadan saya tak akan sepenuhnya sama.
Silaturahmi, Donasi, dan Kenyataan Bahwa Tidak Semua Orang Menyambut Ramadan dari Rumah
Silaturahmi sore itu terasa seperti agenda yang sudah kita kenal betul: duduk, menyapa, tertawa kecil, lalu mendengar sambutan dengan kepala mengangguk pelan. Winners Backyard menjadi ruang yang hangat, secara suhu dan suasana. Namun justru di ruang senyaman itu, kata “rumah” berulang kali muncul dengan makna yang berbeda. Bukan rumah tempat kita pulang setiap hari, melainkan rumah yang masih berupa rencana, target, dan angka-angka yang sedang dikejar agar selesai sebelum Ramadan benar-benar tiba.
Donasi, dalam acara itu, tidak hadir sebagai ajakan heroik atau jargon besar. Ia muncul lewat cerita yang sederhana dan jujur: tentang keluarga yang sudah berbulan-bulan tinggal di tenda, tentang anak-anak yang belajar tidur lebih cepat karena gelap datang lebih awal, dan tentang orang tua yang harus tetap kuat di ruang yang bahkan tidak bisa disebut ruang. Mendengar itu, saya jadi paham bahwa memberi bukan selalu soal berapa banyak yang kita punya, tapi seberapa cepat kita memutuskan untuk peduli.
Di titik itulah saya merasa agak canggung dengan kenyamanan sendiri. Ramadan yang selama ini saya bayangkan dengan meja makan, jadwal buka, dan rutinitas ibadah ternyata tidak berlaku untuk semua orang. Ada yang menyambutnya dengan tikar tipis dan atap darurat. Dan silaturahmi sore itu, tanpa banyak ceramah, mengingatkan saya pada satu hal sederhana: rumah adalah kemewahan yang sering kita anggap biasa, sampai suatu hari ia benar-benar tidak ada.
Dari Jakarta yang Hangat ke Sumatra yang Masih Belajar Bertahan
Jakarta sore itu ramah, bahkan cenderung memanjakan. Jalanan Pondok Pinang masih menyisakan hiruk-pikuk khas ibu kota, tapi di dalam venue, semua terasa rapi dan terkendali. Saya mendengarkan cerita-cerita dari mereka yang baru pulang dari Sumatra, dan di kepala saya muncul kontras yang jujur: antara kota yang terlalu sering mengeluh soal macet dan hujan, dengan daerah yang harus bernegosiasi setiap hari dengan kehilangan.
Cerita dari lapangan tidak disampaikan dengan nada dramatis, justru itu yang membuatnya menempel. Tentang tidur di tenda bersama anak-anak dan lansia, tentang hujan yang tidak bisa dimarahi, dan tentang pagi yang datang tanpa kepastian. Saya menangkap satu benang merah: bertahan bukan pilihan heroik, tapi kewajiban. Mereka tidak sedang mengejar kenyamanan, hanya ingin kembali ke kondisi yang layak disebut hidup normal.
Di ruangan yang aman itu, saya seperti diajak berpindah tempat tanpa benar-benar pergi. Dari Jakarta yang hangat menuju Sumatra yang masih belajar berdiri setelah jatuh berkali-kali. Dan saya sadar, jarak geografis sering kali membuat empati kita melemah. Padahal, satu cerita saja cukup untuk mengingatkan: ketangguhan tidak selalu tampak gagah, kadang ia hadir dalam bentuk kesabaran yang diam-diam melelahkan.
Tentang Zakat, Rumah Sementara, dan Alasan Kita Perlu Bergerak Sekarang
Pada akhirnya, semua cerita sore itu bermuara pada satu hal yang sering kita dengar, tapi jarang kita maknai ulang: zakat dan kepedulian. Di acara itu, zakat tidak dibicarakan sebagai kewajiban administratif, melainkan sebagai jembatan. Jembatan dari mereka yang punya ruang lebih, menuju mereka yang bahkan belum punya ruang untuk sekadar bernaung. Rumah sementara (Rumtara) menjadi simbol paling nyata bahwa bantuan bukan soal sempurna, tapi soal cukup dan tepat waktu.
Saya tersadar, menunda kebaikan sering kali terasa masuk akal di kepala kita. Nanti saja, tunggu lebih longgar, tunggu Ramadan benar-benar datang. Padahal bagi penyintas, waktu berjalan dengan cara yang berbeda. Satu malam di tenda bukan sekadar satu malam; ia adalah akumulasi lelah, cemas, dan harapan yang terus diuji. Bergerak sekarang berarti memotong sedikit dari waktu tunggu mereka, dan itu jauh lebih berarti daripada niat baik yang terlalu lama disimpan.
Karena itu, kalau tulisan ini sampai ke kamu, anggap saja ia bukan ajakan besar, melainkan undangan kecil. Kamu bisa ikut mengambil peran bersama Dompet Dhuafa untuk membantu para penyintas banjir bandang di Sumatra menyambut Ramadan dengan lebih bermartabat. Donasi yang kamu salurkan akan mendukung hunian sementara, pemulihan ekonomi, pendidikan, dan kesehatan mereka yang masih bertahan di tengah keterbatasan.
Salurkan kebaikanmu melalui program PRAY FOR SUMATERA di Dompet Dhuafa.
Ramadan selalu tentang berbagi, dan mungkin, kali ini, tentang memastikan ada lebih banyak orang yang bisa berbagi dari dalam rumah.