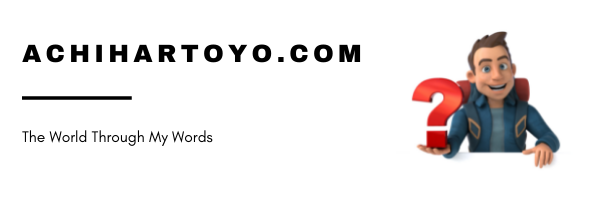“Kadang, yang menyatukan manusia bukan limpahan air, melainkan kesediaan untuk berbagi di tengah kekeringan.”
***
Di sebuah pulau kecil bernama Raijua, air adalah kemewahan yang tak pernah dijanjikan. Tanahnya keras, langitnya jarang meneteskan hujan, dan sumur yang bagi banyak orang hanyalah lubang air di sana menjadi penentu hidup dan mati. Dari satu sumur yang sama, tiga desa berbagi denyut kehidupan. Mereka menimba bukan hanya air, tapi juga kesabaran, kepercayaan, dan kesediaan untuk saling menunggu giliran dalam sunyi yang panjang.
Namun, di tengah segala keterbatasan itu, ada seorang lelaki yang percaya bahwa kebaikan bisa digali sedalam sumber air. Namanya Elkana Goro Leba. Ia tak datang membawa teknologi canggih atau dana besar, hanya keyakinan bahwa manusia bisa bersatu di tengah kekeringan. Ia menggali bukan hanya tanah, tapi juga rasa percaya bahwa di pulau sekering Raijua pun, masih mungkin tumbuh sesuatu yang mengalir, kemanusiaan.
Ketika Air Menjadi Doa
Di tanah yang retak dan berdebu, air bukan sekadar kebutuhan. Ia menjelma doa yang dipanjatkan saban pagi. Dari mulut anak-anak hingga tangan para ibu yang menadah langit, air adalah harapan yang tak pernah benar-benar kering. Setiap tetes yang jatuh ke tanah disambut dengan rasa syukur, seolah alam baru saja berbelas kasih pada mereka yang menunggu dengan sabar.
Ketika hujan datang, orang-orang Raijua tak buru-buru berlari mencari atap. Mereka berdiri di luar rumah, membiarkan tubuh mereka dibasahi. Ada kebahagiaan yang sederhana di sana, yang tak bisa dijelaskan oleh angka curah hujan atau laporan meteorologi. Dalam hujan yang singkat itu, mereka seakan berjumpa dengan sesuatu yang sakral, sesuatu yang lebih besar dari diri mereka sendiri.
Air, bagi mereka, bukan hanya soal hidup. Ia adalah tanda bahwa doa masih punya tempat di bumi yang kian panas dan keras kepala. Ia menjadi pengingat bahwa manusia sesungguhnya kecil di hadapan alam, dan bahwa hidup tak bisa terus diukur dari apa yang bisa dikendalikan. Air datang dan pergi sesuka hatinya, seperti rahmat yang tidak bisa diminta dengan paksa.
Di pagi hari, ketika matahari baru terbit, para perempuan berjalan membawa jerigen kosong ke sumur yang letaknya jauh. Langkah mereka pelan tapi pasti. Ada kesetiaan di dalamnya, seperti ritual yang diwariskan dari satu generasi ke generasi berikutnya. Mereka tahu, perjalanan itu bukan hanya tentang mengambil air, tapi juga tentang menjaga harapan agar tak menguap di bawah terik yang membakar.
Anak-anak kecil mengikuti dari belakang, tertawa kecil sambil bermain dengan bayangan di tanah yang pecah. Mereka belum sepenuhnya mengerti apa arti kesulitan, tetapi sejak dini mereka belajar bahwa air tak datang begitu saja. Bahwa setiap teguk yang mereka minum adalah hasil dari perjalanan panjang, dari keringat dan kebersamaan, dari doa yang tidak berhenti diucapkan.
Maka, di Raijua, air menjadi sesuatu yang suci tanpa perlu disebut demikian. Ia hadir dalam setiap percakapan tentang hidup, dalam setiap kerja sama untuk bertahan. Dan di antara retak tanah yang panjang itu, manusia belajar satu hal yang tak tertulis di kitab mana pun, bahwa kadang yang paling sederhana adalah yang paling menyelamatkan.
Pulau yang Belajar dari Hausnya Sendiri

Foto: Pexels
Raijua adalah cermin kecil dari bumi yang rapuh. Di pulau itu, setiap tetes air membawa kisah tentang perjuangan dan pengharapan. Ketika musim kering datang, tanah merekah seperti luka yang tak sembuh. Namun dari retakan itu pula tumbuh daya tahan, cara hidup yang mengajarkan manusia untuk tidak hanya menunggu, tetapi juga berbuat sesuatu agar kehidupan terus berjalan.
Mereka yang tinggal di Raijua tahu bahwa haus bukan kutukan, melainkan guru yang keras namun jujur. Ia mengajari manusia arti dari cukup, mengingatkan bahwa yang paling penting bukan seberapa banyak air yang dimiliki, tetapi bagaimana ia dijaga dan dibagi. Di tengah panas yang tak kenal ampun, manusia belajar menyesuaikan diri, menakar ulang arti kemewahan, dan menemukan keseimbangan antara harapan dan kenyataan.
Musim kemarau yang panjang sering membuat langit tampak seperti batu biru yang tak mau retak. Namun orang-orang di Raijua belajar membaca tanda-tanda alam dengan mata yang sabar. Mereka tahu kapan harus menampung air, kapan harus berhemat, dan kapan harus berdoa. Dalam kesunyian itu, mereka tidak menyerah pada nasib, melainkan berdamai dengannya.
Pulau itu menjadi ruang belajar bagi banyak hal yang sering dilupakan manusia di tempat lain. Tentang bagaimana alam tidak bisa ditaklukkan, hanya bisa dipahami. Tentang bagaimana kesederhanaan bisa melahirkan kebijaksanaan. Di Raijua, kering bukan berarti mati, melainkan cara alam memanggil manusia untuk kembali mendengar.
Mungkin bagi orang kota, Raijua tampak seperti tempat yang tertinggal. Tapi di balik keterbatasannya, pulau itu menyimpan kedalaman yang sulit ditemukan di tempat lain. Di sana, orang masih saling menyapa tanpa pamrih, masih berbagi air meski hanya seteguk. Mereka hidup dengan pengetahuan kuno yang jarang diajarkan, bahwa dunia hanya bisa bertahan jika manusia saling menolong.
Raijua telah belajar dari hausnya sendiri. Ia tahu bahwa kekurangan bukan akhir dari segalanya, melainkan awal dari pengertian baru tentang hidup. Di tengah tanah yang tandus, manusia menemukan bahwa ketahanan tidak lahir dari kelimpahan, melainkan dari kesediaan untuk tetap berbagi, bahkan ketika yang tersisa hanyalah setetes air.
Satu Sumur untuk Banyak Rasa
Di Raijua, satu sumur bisa berarti kehidupan bagi banyak orang. Tiga desa datang bergantian, membawa ember, jerigen, dan harapan yang sama. Mereka menimba bukan hanya air, tetapi juga kesabaran. Di bibir sumur itu, orang-orang saling menunggu tanpa keluh, saling menatap tanpa curiga. Di antara tali yang berderit dan ember yang turun naik, ada harmoni yang lahir dari keterbatasan.
Air yang ditimba dari sumur itu rasanya sama, tetapi maknanya berbeda bagi setiap orang. Bagi ibu-ibu, itu adalah penawar lelah dan penopang rumah tangga. Bagi anak-anak, itu adalah kesegaran setelah bermain di terik siang. Bagi para lelaki, itu adalah simbol keberlanjutan, bukti bahwa mereka mampu menjaga kehidupan bersama. Air menjadi cermin bagi rasa saling percaya yang tumbuh tanpa janji, hanya dengan keikhlasan.
Tidak ada aturan tertulis di sekitar sumur itu, namun semuanya berjalan dengan tertib. Setiap orang tahu kapan harus menunggu dan kapan harus memberi jalan bagi yang lain. Kepercayaan menjadi hukum yang tidak diucapkan. Tidak ada yang berani melanggar, karena yang dijaga bukan hanya air, tapi juga kehormatan dan kebersamaan.
Dari satu sumur itu pula tumbuh kisah tentang persaudaraan. Mereka yang dulunya berasal dari desa berbeda kini merasa terikat oleh satu kebutuhan yang sama. Dalam kering yang panjang, mereka belajar arti berbagi tanpa menuntut balasan. Air membuat batas-batas administratif menjadi cair, membuat manusia lebih mengenal wajah sesamanya daripada nama desanya.
Ada kesunyian yang hangat di sekitar sumur itu. Suara air yang ditimba seperti irama doa yang pelan. Tidak ada yang terburu-buru, karena setiap giliran adalah kesempatan untuk berbicara, bercanda, atau sekadar saling memahami tanpa kata. Di antara tawa kecil dan percakapan ringan, mereka menemukan bentuk kebahagiaan yang sederhana, yang lahir dari rasa cukup.
Mungkin di tempat lain, air bisa dibeli dan dibagi dengan hitungan liter. Tapi di Raijua, satu sumur menampung lebih dari sekadar air. Ia menyimpan rasa saling percaya, menahan amarah, dan menumbuhkan pengertian. Dari satu sumber kecil itu, lahir sesuatu yang jauh lebih besar dari yang tampak di permukaan, yaitu rasa kemanusiaan yang tidak pernah kering.
Nama yang Mengalir di Antara Batu dan Debu
Elkana Goro Leba bukan sosok yang terbiasa dengan panggung atau sorotan. Ia lahir dan tumbuh di tanah yang keras, di mana air lebih langka dari kabar, dan kerja keras menjadi bahasa sehari-hari. Di Raijua, orang mengenalnya bukan dari gelar atau jabatan, tetapi dari caranya berjalan tanpa banyak bicara, dan dari tangannya yang tak pernah berhenti bekerja menggali sumber kehidupan. Namanya mengalir dari satu mulut ke mulut lain, seperti air yang ia perjuangkan untuk mengalirkan harapan.
Ia tahu bahwa menggali sumur di tanah sekering itu bukan sekadar pekerjaan fisik, tetapi juga ujian keyakinan. Batu, tanah, dan debu adalah teman yang kadang melawan. Tapi Elkana tidak berhenti. Ia percaya bahwa di bawah lapisan keras itu, selalu ada sesuatu yang lembut menunggu ditemukan. Ketekunannya menjadi simbol bahwa kebaikan bukan hasil dari kemudahan, melainkan dari keberanian untuk tidak menyerah pada kenyataan.
Ketika air pertama kali muncul dari tanah, orang-orang berkumpul. Mereka bersorak pelan, tidak dengan gegap gempita, melainkan dengan air mata yang menetes bersama aliran pertama. Bagi mereka, sumur itu bukan sekadar lubang di tanah, tetapi bukti bahwa doa dan kerja bisa berpadu. Elkana berdiri di antara mereka, diam, membiarkan air itu berbicara lebih keras daripada dirinya.
Waktu berlalu, dan nama Elkana tetap disebut di antara percakapan sederhana di serambi rumah. Ia tidak meninggalkan tugu peringatan atau prasasti, hanya jejak telapak kaki dan mata air yang terus hidup. Di tempat di mana angin membawa debu dan garam laut, kisahnya menjadi bagian dari ingatan kolektif, sebuah cerita yang diwariskan dengan nada lembut kepada anak-anak.
Mungkin di kota, nama seperti Elkana Goro Leba tak akan masuk berita. Tapi di Raijua, ia telah menulis sejarah kecil yang tak akan dihapus waktu. Ia menunjukkan bahwa kepahlawanan tidak harus besar, cukup jujur dan bertahan di tempat yang orang lain anggap sepi. Ia membuat air tak lagi sekadar benda cair, melainkan perwujudan kasih yang tak kenal pamrih.
Dan di antara batu dan debu yang terus berubah arah angin, nama Elkana mengalir seperti sungai kecil yang tidak kering. Ia menjadi bagian dari tanah, dari udara, dari cerita yang diulang setiap kali seseorang menimba air. Nama yang mungkin tak terukir di batu, tetapi melekat di hati mereka yang pernah merasakan hasil jerih payahnya.
Air sebagai Bahasa yang Menyatukan
Air tidak pernah memilih jalan, ia hanya tahu caranya mengalir. Ia pergi ke tempat yang paling rendah, menyentuh tanah, batu, dan akar dengan kesetiaan yang sama. Dari situlah manusia seharusnya belajar, bahwa ketinggian bukan ukuran kemuliaan. Justru dalam kerendahan hati, sesuatu yang besar bisa tumbuh, seperti sungai yang selalu berawal dari tetes kecil.
Di Raijua, air menjadi bahasa yang dimengerti semua orang. Ia tak mengenal perbedaan desa atau garis batas. Siapa pun yang datang ke sumur membawa wadah, berhak menimba dengan cara yang sama. Di tempat itu, tidak ada yang lebih dulu atau lebih pantas. Air mengajarkan keadilan dengan cara yang lembut, tanpa perintah, tanpa aturan tertulis.
Ketika ember bersentuhan di bibir sumur, tidak terdengar nada tinggi, hanya sapaan pelan yang hangat. Orang-orang belajar berbicara dengan kesabaran, karena mereka tahu setiap orang datang membawa dahaga yang berbeda. Di antara mereka, air menjadi penerjemah yang paling setia, mengalirkan pengertian tanpa perlu kata.
Bagi masyarakat Raijua, berbagi air sama artinya dengan berbagi hidup. Di tengah kekeringan, mereka tahu bahwa yang membuat mereka tetap utuh bukan semata sumber air itu sendiri, melainkan kesediaan untuk saling menolong. Air menjadi alasan untuk bertemu, untuk saling mengenal, untuk mengingat bahwa manusia diciptakan bukan untuk hidup sendiri.
Air juga menyimpan pelajaran tentang waktu. Ia bergerak perlahan, kadang tertahan, kadang menghilang, namun selalu kembali dengan cara yang tak terduga. Seperti hubungan antar manusia yang diuji oleh jarak dan musim, tapi menemukan jalannya untuk bersatu kembali. Dalam setiap putaran itu, air mengajarkan kesetiaan yang tak memerlukan pengakuan.
Dan ketika seseorang menimba air di Raijua, sesungguhnya ia sedang menimba kebersamaan. Setiap tetes yang jatuh ke wadah adalah peringatan halus bahwa hidup akan selalu lebih mudah ketika dijalani bersama. Di pulau yang keras dan kering itu, air telah menjadi bahasa yang menyatukan, meneguhkan bahwa yang paling murni dari manusia adalah kemampuannya untuk memberi tanpa pamrih.
Sebuah Penghargaan yang Mengalir Lebih Jauh

Elkana Goro Leba tidak pernah bermimpi tentang penghargaan. Ia hanya ingin melihat air mengalir di tanah yang kering, dan wajah-wajah di desanya tersenyum tanpa takut kehausan. Namun, apa yang ia lakukan di Raijua melampaui batas tempat itu sendiri. Kisahnya mengalir keluar dari pulau kecilnya, menyentuh hati banyak orang yang mungkin tak pernah tahu bagaimana rasanya menimba air dari satu sumur untuk tiga desa.
Melalui SATU Indonesia Awards, namanya kini disebut dalam ruang yang lebih luas. Tapi penghargaan itu tidak mengubahnya. Ia tetap bekerja dengan cara yang sama, sederhana dan tenang. Penghargaan hanya menjadi jembatan agar lebih banyak orang mengenal arti perjuangan yang lahir dari keterbatasan. Di balik sorotan, Elkana tetap menjadi air yang mengalir pelan, memberi kehidupan tanpa banyak suara.
Pengakuan itu membawa pesan yang lebih dalam daripada sekadar apresiasi. Ia mengingatkan kita bahwa perubahan besar sering dimulai dari tindakan kecil yang dilakukan dengan hati. Dari sumur di Raijua, kita belajar bahwa kerja kemanusiaan tidak membutuhkan panggung, hanya keyakinan bahwa kebaikan selalu menemukan jalannya untuk terlihat, bahkan di tempat paling sunyi.
Di balik setiap penghargaan, ada banyak tangan yang bekerja tanpa dikenal. SATU Indonesia Awards menjadi ruang untuk menampung cerita-cerita semacam itu, tentang orang-orang yang memilih diam tetapi terus bergerak. Dari mereka, kita belajar arti ketulusan yang sesungguhnya, bahwa memberi tidak perlu disertai pengumuman, cukup dilakukan dengan keyakinan bahwa hidup akan lebih indah jika dibagi.
Dan mungkin itulah makna terdalam dari penghargaan seperti ini. Ia bukan tentang siapa yang menang, melainkan tentang siapa yang mengingatkan kita untuk tidak berhenti berbuat baik. Dari tanah Raijua yang kering, dari sumur yang menghidupi tiga desa, dari tangan seorang lelaki bernama Elkana Goro Leba, kita melihat bahwa air dan kemanusiaan sama-sama memiliki sifat yang luhur, keduanya hanya ingin terus mengalir.